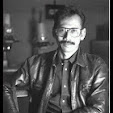KASUS PEMBELIAN SAHAM PT NEWMONT NUSA TENGGARA OLEH
PEMERINTAH
Untuk menyongsong keputusan
Mahkamah Konstitusi pada hari ini (31 Juli 2012), mungkin ada manfaatnya bila penjelasan
tentang kasus Newmont terlampir saya unggah dalam blog khusus ini. Terlepas keputusan
apa yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi, saya sangat berharap hendaknya berbagai
pihak dapat memahami secara utuh masalah yang sebenarnya terjadi antara pihak Eksekutif
dan pihak Lembaga Legislatif dalam kasus ini. Hendaknya berbagai pihak memiliki
konsistensi untuk melihat kasus ini secara proporsional dari sudut pandang Hukum
Tata Negara, khususnya Hukum Keuangan Negara. Bukan dari sudut pandang lain, terutama
dari sisi kepentingan politik.
Salam,
SS.
Yang Mulia Ketua dan para
Hakim Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi. Pemohon, Termohon I, Termohon II, Para Ahli, dan
Hadirin sekalian yang dimuliakan.
Assalamualaikum warrahmatullahi
wa barakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
Pertama-tama,
perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada Hakim Panel Mahkamah Konsitusi yang telah mengijinkan saya sebagai Ahli
Hukum Keuangan Negara dari pihak Termohon II (Badan pemeriksa Keuangan) untuk
menyampaikan penjelasan saya dalam kasus pembelian saham PT NEWMONT NUSA TENGGARA sebanyak 7% oleh pihak Pemohon
(Pemerintah).
Kedua, ringkasan sebagian
pendapat saya telah disampaikan sebelumnya oleh Rektor Universitas Patria Artha
Makassar kepada para Termohon yang mungkin materinya telah disampaikan dalam
forum ini, dan pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan
secara langsung.
Yang Mulia Ketua dan para
Hakim Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi dan para hadirin yang saya hormati
Kasus yang terjadi antara
Pemohon, Termohon I, dan Termohon II adalah sebuah kasus yang terjadi dalam lingkup Hukum
Keuangan Negara. Yaitu merupakan kasus yang terjadi dalam hubungan antara
Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif dalam rangka penetapan Undang-undang
APBN serta dalam rangka pelaksanaan UU APBN.
Oleh karena itu, tanpa
memiliki pretensi yang berlebihan, dan mengurangi arti penjelasan dari sudut
disiplin ilmu lainnya, saya berpendapat bahwa penjelasan dari sudut Ilmu Hukum
Keuangan Negara sudah selayaknya dipandang memiliki relevansi yang relatif
tinggi dibandingkan dengan penjelasan dari sudut disiplin ilmu lainnya. Hal ini
tentunya dengan mengacu pada azas proporsionalitas, yaitu dengan menempatkan
disiplin Ilmu Hukum Keuangan Negara sebagai instrumen untuk melakukan analisis
terhadap permasalahan yang timbul dalam bidang Hukum Keuangan Negara.
Dalam praktek selama ini,
mengingat disiplin Ilmu Hukum Keuangan Negara di Indonesia belum berkembang, sekedar
untuk mencari pembenaran bahwa masalah-masalah Keuangan Negara telah dianalisis
dari aspek hukum, kasus-kasus yang terjadi dalam lingkup Keuangan Negara seringkali
dianalisis oleh berbagai pihak dengan menggunakan sudut pandang dari berbagai
disiplin ilmu hukum, misalnya : Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara,
Hukum Bisnis, Hukum Pidana, dan juga
Hukum Perdata. Padahal, ini adalah satu pemahaman yang kurang tepat atau kalau
boleh dikatakan, keliru.
Sehubungan dengan itu,
perkenankanlah saya menyampaikan penjelasan kasus tersebut dari sudut Ilmu
Hukum Keuangan Negara sebagaimana yang telah saya pelajari dan dalami selama
ini, baik sebagai akademisi maupun sebagai praktisi. Sebagai praktisi, yaitu ketika saya ditunjuk
sebagai Ketua Tim Kecil Penyusunan Rancangan
Undang-undang Bidang Keuangan Negara yang kemudian menjadi Undang-undang No. 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
Yang Mulia Ketua dan para
Hakim Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi dan para hadirin yang saya hormati
Menurut studi Ilmu Hukum Keuangan Negara, Pengelolaan
Keuangan Negara terbagi dalam dua aspek (sisi), yaitu : aspek politis dan aspek
administratif.
Dalam
kajian Ilmu Hukum Keuangan Negara, aspek politik keuangan negara ini secara substansi mengatur hubungan hukum
antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dalam rangka penyusunan dan
penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Secara
konkrit, aspek politis keuangan negara tersebut terkait dengan pelaksanaan
pemikiran/ ide yang terkandung dalam undang-undang dasar. Yakni, mengatur
bagaimana amanah undang-undang dasar yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan
negara dan pemenuhan hak-hak azasi warga negara harus diwujudkan.
Amanah
undang-undang dasar dimaksud diwujudkan dalam
bentuk kegiatan pengelolaan rumah tangga negara, baik dari aspek kegiatan yang
akan dilaksanakan maupun dari aspek
pembiayaannya (financing). Dari aspek pembiayaan, pada hakekatnya,
menjawab pertanyaan bagaimana pemerintah dapat membiayai kegiatan pemerintah
dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan hak-hak
azasi warga negara.
Di
negara demokratis, peran rakyat melalui sistem perwakilannya (lembaga
legislatif) dalam pelaksanaan aspek politis keuangan negara ini sangat dominan
dibandingkan peran pemerintah (lembaga eksekutif) yang, pada prinsipnya, hanya merupakan pelaksana.
Mewakili rakyat, setiap tahun, lembaga legislatif membuat kesepakatan dengan
lembaga eksekutif mengenai rencana kerja yang harus dilakukan dalam rangka
mewujudkan amanah undang-undang dasar tersebut di atas. Kesepakatan tersebut
bukan saja berisi kegiatan-kegiatan yang harus dan akan dilaksanakan, akan
tetapi juga berisi bagaimana cara pembiayaannya. Dalam arti, dari mana
pendanaan untuk membiayai kegiatan tersebut dapat diperoleh. Kesepakatan inilah
yang kemudian dikenal secara luas dengan istilah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
Dengan
demikian, secara politis, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara adalah suatu bentuk kesepakatan antara lembaga
legislatif dan lembaga eksekutif yang berisi rencana kegiatan dan cara
pembiayaannya. Dalam kesepakatan tersebut lembaga legislatif memberikan
kewenangan sepenuhnya kepada lembaga eksekutif untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan yang tertuang didalamnya, di satu sisi, dan memberikan
kewenangan untuk mengupayakan pendanaan dalam rangka membiayai kegiatan
tersebut. Inilah yang kemudian dikenal
dengan istilah autorisation parlementaire.
Dalam bahasa yang lebih umum dikenal oleh masyarakat luas inilah inti
dari hak budget lembaga legislative.
Sebagaimana laiknya suatu
kesepakatan, kesepakatan antara kedua lembaga politik tersebut juga memiliki
konsekwensi logis dalam bentuk hak dan kewajiban bagi kedua-belah
pihak.
Di pihak lembaga legislatif, hak
yang timbul dengan adanya kesepakatan dimaksud adalah hak untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan
yang telah dituangkan dalam suatu produk perundang-undangan. Hak pengawasan
lembaga legislatif, pada hakekatnya, mencakup baik pada sisi pelaksanaan
pengeluaran negara, maupun pada sisi penerimaan negara.
Hal ini oleh
karena melalui kedua sisi itulah pelaksanaan persetujuan diwujudkan.
Hak lainnya yang sangat
penting artinya bagi lembaga legislatif adalah hak untuk meminta pertanggungjawaban
kepada lembaga eksekutif terhadap pelaksanaan rencana kerja maupun rencana
pembiayaannya. Sementara itu, kewajiban yang harus dilakukan oleh lembaga
tersebut
adalah memberikan dukungan maupun konsultasi agar pelaksanaan kesepakatan
tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
Di pihak lain, seperti hakekat nama yang melekat, lembaga eksekutif, pada
prinsipnya, adalah pelaksana dari keputusan yang telah disetujui
dan ditetapkan
oleh rakyat melalui lembaga perwakilannya. Oleh sebab itu, bila
diperhatikan, hak lembaga eksekutif
adalah hak
untuk melaksanakan kesepakatan
yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan mewujudkan semua rencana yang
terkandung di dalamnya.
Terkait dengan peran lembaga
eksekutif tersebut,
semua kebijakan yang disusun oleh pemerintah adalah kebijakan operasional dalam
rangka pelaksanaan kesepakatan. Bukan merupakan kebijakan yang bersifat
konsepsional yang berujung pada perubahan substansi kesepakatan.
Terhadap kenyataan ini,
banyak ahli berpendapat bahwa hak
yang dimiliki oleh lembaga eksekutif dalam hal ini tidak lebih hanya merupakan suatu bentuk kewajiban. Bukan hak dalam
arti yang sebenarnya, karena ternyata lebih cenderung
berupa kewajiban untuk melaksanakan perintah/ kesepakatan.
Di sisi lain, kewajiban
lembaga eksekutif adalah menyusun pertanggungjawaban pada akhir periode atas
berbagai program dan kegiatan yang telah disetujui lembaga legislatif.
Pertanggungjawaban dimaksud, disamping mencakup kinerja lembaga eksekutif dalam
mewujudkan program-program kerja yang telah direncanakan (performance
responsability), juga mencakup pertanggungjawaban keuangan (financial responsability),
yang terdiri dari pertanggungjawaban atas pemungutan dana-dana yang bersumber
dari masyarakat dan penggunaan dana tersebut untuk membiayai
kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan.
Pembagian peran antara
lembaga legislatif dan lembaga eksekutif sebagaimana dikemukakan di atas, telah memberikan inspirasi
bagi lahirnya prinsip transparansi anggaran (fiscal
transparency) di era modern
yang pada intinya, antara lain, menekankan adanya kejelasan peran antara pihak yang mengusulkan
dan pihak yang memutuskan; antara pihak pengambil keputusan
dan pihak pelaksana keputusan.
Selanjutnya, bila
dicermati, pola dan mekanisme yang berkembang dalam penyusunan anggaran antara
dua lembaga politik itulah yang kemudian juga melahirkan berbagai prinsip dasar dalam pengelolaan anggaran
negara yang hingga kini masih tetap dipertahankan. Prinsip-prinsip dimaksud,
pada hakekatnya, merupakan alat bagi lembaga legislatif untuk dapat melakukan pengawasan secara
efektif dan efisien terhadap pelaksanaan
anggaran negara yang dilakukan
oleh lembaga eksekutif.
Prinsip-prinsip dasar yang kemudian dikenal sebagai golden principles of
Budget execution tersebut terdiri dari: prinsip-prinsip prealable,
annualitas, unitas, spesialitas/ spesifitas, dan prinsip universalitas.
Sebagai
contoh, dapat disebutkan di sini misalnya, prinsip
anterioritas atau prinsip prealable yang menekankan bahwa anggaran negara harus
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari lembaga legislatif sebelum
dilaksanakan. Kemudian, prinsip
anualitas atau prinsip periodisitas yang menyatakan
bahwa anggaran negara harus dilaksanakan dalam suatu periode tertentu yang
ditandai dengan titik awal dimulainya anggaran (suatu tanggal tertentu) dan
diakhiri pada suatu tanggal tertentu. Selanjutnya, prinsip spesialitas merupakan prinsip yang menekankan bahwa alokasi
dana anggaran harus spesifik atau terinci berdasarkan fungsi, organisasi hingga
ke jenis pengeluaran/ belanja.
Prinsip-prinsip itulah yang memberikan karakter pada anggaran pendapatan
dan belanja Negara (APBN) sehingga memiliki ciri-ciri, antara lain, single periode, artinya bahwa
pengeluaran tidak dapat dilakukan secara akumulasi dari otorisasi yang
diberikan dalam beberapa tahun; dan specified,
artinya bahwa alokasi pengeluaran tidak dapat diberikan secara global,
melainkan harus bersifat rinci dan spesifik. Walaupun, karena alasan teknis,
lembaga legislatif tidak jarang terpaksa memberikan alokasi yang bersifat conditional dengan
jumlah global. Namun demikian, alokasi dimaksud baru
dapat dilaksanakan pihak eksekutif, bilamana kondisi yang dipersyaratkan
terpenuhi dan rincian
kegiatan yang diajukan disetujui oleh lembaga legislatif.
Prinsip-prinsip dasar yang
kemudian dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan anggaran
pendapatan dan belanja negara tersebut, bila dicermati, ternyata merupakan pilar
pengawasan bagi lembaga legislatif terhadap pelaksanaan kesepakatan dengan
pihak eksekutif. Artinya, prinsip-prinsip
dasar dimaksud diciptakan untuk memberikan batasan kepada lembaga eksekutif
sebagai pelaksana agar tidak menyimpang dari arah dan tujuan yang telah
ditetapkan.
Lebih dari itu,
bila dicermati lebih lanjut, bahwa salah satu prinsip tersebut, yaitu prinsip
anterioritas atau prinsip prealable, telah
menempatkan lembaga legislatif dalam posisi yang lebih tinggi/ lebih kuat
dibandingkan posisi lembaga eksekutif. Dalam praktek, hal ini diwujudkan
dengan adanya berbagai ketentuan dalam perundang-undangan terkait dengan
pengelolaan anggaran dan belanja negara yang melarang untuk melakukan
perikatan bila tidak tersedia dana dalam anggaran.
Sementara itu, bagi
lembaga legislatif sendiri, prinsip-prinsip tersebut dijadikan sebagai ukuran
dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan maupun kepatuhan
lembaga eksekutif terhadap berbagai keputusan lembaga legislatif.
Yang Mulia Ketua dan para
Hakim Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi dan para hadirin yang saya hormati
Bila aspek politis keuangan
negara mengatur hubungan hukum antara lembaga politis dalam penyusunan dan
penetapan APBN, aspek administratifnya
mengatur hubungan hukum antara berbagai instansi dalam lembaga eksekutif dalam
melaksanakan APBN.
Terkait dengan itu, dapat
dikatakan bahwa berbagai tindakan para
pejabat publik dalam lingkup administratif hanya merupakan operasionalisasi keputusan politis,
yaitu keputusan yang telah dituangkan dalam APBN.
Tindakan kepala pemerintahan,
selaku pimpinan lembaga eksekutif, diwujudkan dalam bentuk penerbitan dokumen
pelaksanaan anggaran yang memungkinkan dilaksanakannya APBN. Tindakan ini dalam
Hukum Keuangan Negara dikenal dengan pemberian autorisation presidentiel atau
autorisation gouvernementale.
Selanjutnya, dalam rangka
pelaksanaan APBN dimaksud diterbitkanlah berbagai surat keputusan yang memiliki
karakter otorisasi yang dijadikan dasar bagi pelaksanaan pengeluaran negara.
Penerbitan surat keputusan dimaksud merupakan pemenuhan unsur untuk melengkapi
langkah operasionalisasi keputusan politis. Dengan demikian, penerbitan
berbagai (surat) keputusan oleh pejabat publik dalam pelaksanaan APBN bukan merupakan
keputusan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan akibat dari suatu keputusan
politis yang telah diambil dalam rangka penyusunan dan penetapan APBN.
Satu hal yang menjadi kunci
dalam aspek administratif ini adalah bahwa pelaksanaan pembiayaan kegiatan
dimaksud harus mengikuti prosedur baku dan berpatokan pada norma-norma
pengelolaan keuangan negara agar terhindar dari kemungkinan terjadinya kerugian negara.
Oleh karena itu, pemikiran utama
yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat / pengelola keuangan negara
dalam melakukan tindakan pengeluaran negara adalah dengan menghindarkan
terjadinya kerugian negara.
Yang Mulia Ketua dan para
Hakim Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi dan para hadirin yang saya hormati
Sudut
pandang dari dua aspek sebagaimana tersebut di atas ditrapkan pula di
Indonesia. Bahkan, di Indonesia pemisahan dimaksud diwujudkan secara tegas
dengan menempatkan kedua aspek pengelolaan keuangan negara tersebut dalam undang-undang yang berbeda. Yaitu,
aspek politis pengelolaan keuangan negara dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, sedangkan aspek administratifnya dalam Undang-undang
No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Dalam
kedua undang-undang tersebut di atas diatur pengelolaan Keuangan Negara yang ditrapkan di Pemerintah Pusat dan juga
pengelolaan Keuangan Negara yang ditrapkan di Pemerintah Daerah. Hal itu
dilakukan, karena konsepsi pengelolaan keuangan daerah, pada hakekatnya,
merupakan konsepsi pengelolaan keuangan
negara pada umumnya yang ditrapkan dalam wilayah yang terbatas, yaitu dalam wilayah Propinsi, Kabupaten, maupun
Kotamadya.
Atas dasar uraian yang dipaparkan di atas, menurut kenyataannya Undang-undang No. 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara bukanlah mengatur hal yang sama dengan Undang-undang No. 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang
No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada prinsipnya, mengatur operasionalisasi keputusan politis yang telah
dituangkan dalam Undang-undang
APBN
yang telah diputuskan sesuai Undang-undang
No. 17 Tahun 2003.
Dengan demikian, Undang-undang
Perbendaharaan Negara tidak mengatur hal yang sama dengan yang diatur dalam
Undang-undang
Keuangan Negara. Dengan mengacu pada materi pengaturan dan juga hubungan di atas, Undang-undang No. 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bukanlah
merupakan lex spesialis
Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Oleh karena itu, bila terdapat pihak-pihak tertentu yang menyatakan
bahwa Undang-undang
No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan lex spesialis dari Undang-undang
No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sama sekali tidak berdasar. Dalam hal ini hampir
dapat dipastikan bahwa pihak-pihak tersebut kurang memahami historic and philosophical back ground, raison d’etre, maupun nature dari Undang-undang Perbendaharaan tersebut.
Yang Mulia Ketua dan para
Hakim Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi dan para hadirin yang saya hormati
Bila dicermati secara teliti, konsep
pemikiran tentang pengelolaan keuangan negara dalam rangka membiayai kegiatan
pemerintahan negara sebagaimana dikemukakan di atas terkristalisasi dalam
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45), yaitu dalam Bab VIII pasal 23. Pasal ini
pada hakekatnya memuat inti utama pengelolaan keuangan negara, yaitu hubungan
hukum antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dalam penyusunan dan penetapan
APBN.
Berbeda dengan undang-undang dasar
beberapa negara maju (dan juga UUDS 1950) yang mengatur masalah hubungan ini
secara luas dan rinci, UUD 45 yang secara historis penyusunannya yang sangat
singkat memang diciptakan dengan karakter yang simple dan fleksibel. Oleh sebab itulah, dalam ayat 4 pasal
tersebut (kini pasal 23 c) diamanatkan
agar hal-hal lain mengenai keuangan
negara diatur dengan undang-undang.
Artinya, dengan tetap mempertahankan karakter UUD 45, pengaturan lebih lanjut
dan rinci tentang pengelolaan keuangan negara dilakukan dalam tataran ketentuan
yang lebih rendah, yaitu undang-undang.
Pengaturan lebih lanjut yang
dimaksudkan dalam UUD 45 tersebut bukan saja menyangkut sisi politis
pengelolaan keuangan negara, melainkan juga menyangkut sisi administratifnya.
Oleh sebab itu, kemudian lahirlah
Paket Undang-undang Bidang Keuangan Negara yang terdiri dari Undang-undang No.
17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
Walaupun inti pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan negara dilakukan melalui APBN, dalam penjelasan
Umum angka 3 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara tersebut
dinyatakan bahwa lingkup pengelolaan keuangan negara, pada prinsipnya, dapat
dikelompokkan ke dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal,
sub bidang pengelolaan moneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang
dipisahkan. Dua sub bidang yang pertama memiliki karakter pemerintah dalam arti
sebenarnya, karena merupakan pemegang kebijakan negara. Sementara itu, sub
bidang ketiga merupakan perwujudan pemerintah sebagai swasta.
Dengan tetap mengacu pada pasal 23
dan pasal 23 c UUD 45, kendati motivasi dan tata kelola (unsur) keuangan negara
di masing-masing sub bidang memiliki perbedaan, pengawasan DPR, baik bersifat pre maupun post, mutlak diperlukan. Pengawasan DPR bukan hanya terbatas pada
pengelolaan di masing-masing sub bidang, mutasi unsur-unsur keuangan negara
dari satu sub bidang ke sub bidang lainnya, secara prinsip, memerlukan ijin
DPR. Hal ini merupakan konsekuensi dari pemberian kewenangan legislatif (autorisation parlementaire) kepada
lembaga eksekutif.
Secara historis, sebagaimana
dikemukakan dalam bagian sebelumnya, hubungan antara lembaga legislatif dan
lembaga eksekutif dalam penetapan APBN memang sangat spesifik. Bila lembaga
eksekutif yang memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan (undang-undang)
APBN hal tersebut semata-mata hanyalah karena alasan teknis pelaksanaan. Namun,
kekuasaan anggaran yang sebenarnya terletak di tangan lembaga legislatif. Hal
ini jelas tergambar dalam penjelasan di atas, yang ternyata juga dinyatakan
dalam UUD 45.
Undang
Dasar Tahun 1945 memuat norma yang mengatur bahwa APBN ditetapkan setiap tahun
dengan undang-undang. Rancangan Undang-Undang APBN diajukan oleh Presiden untuk
dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan dewan daerah. Apabila DPR
tidak menyetujui RAPBN yang diajukan oleh Presiden maka Presiden menjalankan
APBN tahun yang lalu.
Oleh sebab itu, hubungan lembaga
legislatif dan lembaga eksekutif dalam hal penetapan UU APBN tidak didasarkan
pada prinsip kesetaraan, melainkan lebih bersifat sub-ordonatif, yaitu yang
satu lebih tinggi dari yang lain.
Bila diperhatikan, sifat khusus APBN tersebut
sebagai undang-undang dibandingkan dengan undang-undang lain pada umumnya,
bukanlah terletak pada proses penyusunan maupun penetapannya, melainkan pada
sifat UU APBN itu sendiri yang merupakan acte
condition (beschiking), dan bukan
merupakan acte regle.
Yang Mulia Ketua dan para
Hakim Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi dan para hadirin yang saya hormati
Setelah APBN ditetapkan, kekuasaan
pelaksanaannya berada di tangan kepala pemerintahan, yaitu Presiden. Praktek
seperti ini, yang merupakan best practice
dalam pengelolaan keuangan negara yang dilakukan di berbagai negara, telah dilaksanakan jauh sebelum lahirnya Undang-undang
No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yaitu sejak kemerdekaan dengan
mendasarkan pada ketentuan pasal 25 Indonesische Comptabiliteits Wet (ICW
1925).
Namun, dengan mengacu pada pasal 4 UUD 1945, terkait dengan kekuasaan Presiden dalam pengelolaan
Keuangan Negara tersebut, PROF.
DR. BAGIR MANAN, sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara, dalam workshop yang
diselenggarakan bersama antara Tim Pembahas Paket RUU Bidang Keuangan Negara dengan Universitas Pejajaran pada
tanggal 27 Januari 2003 di Bandung memberikan pendapatnya dengan rumusan sebagai
berikut :
“Presiden
selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara
sebagai bagian dari kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan”.
Dengan berpatokan pada konsepsi bahwa dalam konteks
ini negara merupakan Subyek/ Pengelola Keuangan Negara, yaitu sebagai otoritas yang memiliki tugas dan
kewajiban menjamin tersedianya layanan kepada masyarakat sebagaimana
diamanatkan oleh undang-undang dasar, memiliki konsekuensi logis bahwa
pengelolaan keuangan negara dimaksud harus dilakukan melalui suatu sistem yang
dikenal dengan sistem anggaran pendapatan dan belanja negara.
Pengelolaan keuangan negara melalui sistem anggaran
pendapatan dan belanja negara, pada hakekatnya menghendaki bahwa pengelolaan
keuangan negara harus dilakukan melalui suatu siklus yang disebut dengan siklus
APBN, dan pengelolaan tersebut mencakup lingkup politis dan juga lingkup
administratif.
Sehubungan dengan itu, dalam Tata Kelola Keuangan
Negara, harus memiliki ciri-ciri :
·
Kekuasaan
pengelolaan Keuangan Negara merupakan sebagian dari kekuasaan pemerintahan
·
Kekuasaan
atas pengelolaan Keuangan Negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara
·
Dalam
rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara,
setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Oleh
karena itu, dengan mengacu pada gagasan/ pandangan sebagaimana dikemukakan di
atas, disusunlah butir-butir tersebut dalam pasal-pasal draft RUU Keuangan
Negara.
Selanjutnya,
setelah melalui pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan RUU dimaksud
ditetapkan sebagai undang-undang, yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,
kini dapat dilihat bahwa:
1. salah
satu makna kekuasaan yang terkandung dalam pasal 4 UUD 1945 tersebut, yang
digunakan sebagai ciri tata kelola keuangan negara, kemudian dituangkan dalam pasal 6 ayat (1).
2. selanjutnya,
terkait dengan kekuasaan Presiden dalam pemerintahaan negara tersebut, dalam
pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara
dimaksud digunakan untuk
mencapai tujuan bernegara.
3. sebagai kata kunci, sehubungan dengan kekuasaan
Presiden sebagaimana dimaksud di atas, pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa, dalam
rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara,
setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dari
uraian yang disampaikan di atas secara jelas dapat ditelusuri bahwa, alur
logika yang diikuti dalam menetapkan/ menyusun kekuasaan dan pengelolaan keuangan negara hanya terarah pada Bab VIII UUD 1945,
yaitu pasal 23.
Khusus,
dalam penyusunan RUU
Keuangan Negara dimaksud alur pikir para penyusun, sesuai dengan makna yang
terkandung dalam pasal 4 UUD 1945 itu sendiri, tidak pernah mengkaitkan
kekuasaan pemerintahan dengan pasal 33 UUD 1945.
Dengan demikian, pemahaman terhadap konsepsi
Keuangan Negara harus dilakukan secara
utuh, mulai dari subyek, obyek, tata kelola, dan tujuannya.
Berkaitan dengan itu, Keuangan Negara
harus dipahami bukan sekedar sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1
Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, melainkan harus
dikaitkan dengan pasal-pasal berikutnya secara mengalir, yaitu dengan
pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, dan pasal 15.
Dengan pemahaman yang utuh dan mengalir
tersebut dapatlah dipahami bahwa Keuangan Negara merupakan asset negara yang
bersifat aktif. Oleh karena itu, masalah-masalah Keuangan Negara semata-mata
hanya didasarkan pada amanah sebagaimana tertuang dalam Bab VIII UUD 45. Tidak
terkait dengan pemahaman tentang kekayaan negara sebagaimana dimaksudkan dalam
pasal 33 UUD 45 yang bersifat potensi (pasif), seperti misalnya: kekayaan alam
yang berupa deposit tambang, kekayaan di laut, dlsb.
Yang Mulia Ketua dan para
Hakim Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi dan para hadirin yang saya hormati
Selama ini, berbagai
pihak telah mengartikan secara salah peran Menteri Keuangan dalam pengelolaan
Keuangan Negara. Menteri Keuangan dalam pengelolaan Keuangan Negara selalu
diartikan sebagai Bendahara Umum Negara. Padahal, dalam hal tertentu, Menteri
Keuangan bertindak selaku pembantu Presiden yang menangani masalah-masalah
Keuangan Negara. Dalam perannya yang demikian, Menteri Keuangan adalah Menteri
Teknis sebagaimana menteri lainnya.
Kedudukan Menteri Keuangan
selaku BUN adalah ketika bertindak selaku Pejabat Perbendaharaan saat
berhadapan dengan Menteri Teknis selaku Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan
APBN. Kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN bersifat limitatif sebagaimana
dinyatakan dalam pasal 7 Undang-undang
No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
Peran Bendahara Umum Negara pada
prinsipnya tidak berbeda dengan Bendahara yang ada di berbagai kementrian/
lembaga, namun memiliki cakupan tugas yang lebih luas dan komprehensif yang
meliputi pengelolaan uang, kekayaan, utang, dan piutang. Dalam hal ini perlu
digarisbawahi bahwa, kewenangan Bendahara
Umum Negara untuk menempatkan uang dan melakukan investasi sangat dibatasi, karena hanya
merupakan tindakan dalam pengelolaan kas (cash
management) untuk mencegah terjadinya idle
cash.
Oleh sebab itu, Undang-undang No. 17
Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara menggunakan terminologi ‘ Pemerintah’ dan ‘Menteri
Keuangan’.
Terminologi ‘Pemerintah‘ digunakan ketika
tindakan/ keputusan di bidang keuangan negara tersebut dilakukan oleh Presiden
yang pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Menteri Teknis yang
menangani masalah-masalah Keuangan Negara atau oleh Menteri Teknis lainnya.
Dalam operasi pencairan dananya sudah tentu akan dilakukan oleh Bendahara Umum
Negara yang dalam hal ini adalah juga
Menteri Keuangan, yang dalam praktek keseharian dilakukan oleh
pembantunya (Dirjen. Perbendaharaan).
Sedangkan terminologi ‘Menteri
Keuangan’ digunakan ketika tindakan/ keputusan di bidang keuangan negara
tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
Hal inilah yang harus dipahami,
sehingga tidak terjadi kerancuan ketika membaca Undang-undang No. 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara :
-
pasal
7 ayat (2) huruf h yang berbunyi : Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menempatkan uang negara dan
mengelola/ menatausahakan investasi;
dibandingkan dengan
-
pasal
41 ayat (1) yang berbunyi : Pemerintah
dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi,
sosial dan/ atau manfaat lainnya.
Maksud yang terkandung dalam pasal 41
ayat (1) tersebut adalah jelas bukan dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku
BUN, melainkan oleh Menteri Teknis lainnya yang bertindak atas nama Pemerintah yang
menangani masalah-masalah terkait dengan kegiatan investasi dengan motif
mencari keuntungan, yaitu Menteri BUMN.
Hal ini tentunya sejalan dengan motif
kegiatan pemerintah dalam pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan,
dalam hal ini Kementrian Keuangan, untuk penyelenggaraan layanan publik yang
bersifat non profit oriented.
Berdasarkan penjelasan tersebut di
atas dan dihubungkan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara pasal 68 dan 69 keberadaan Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) pada saat ini di Kementrian Keuangan adalah sangat janggal.
Alasan yang dapat dikemukakan
mengenai hal tersebut antara lain adalah bahwa PIP sebagai BLU seharusnya
bercirikan sebagai institusi pemerintah penyedia layanan publik yang tidak
berorientasi pada profit (not for profit).
Kenyataannya, sebagai lembaga investasi, by
nature PIP merupakan institusi yang berorientasi pada pemupukan keuntungan (profit oriented).
Di awal kelahirannya, ketika masih
bernama Badan Investasi Pemerintah (BIP) dan bernaung di bawah Ditjen.
Perbendaharaan yang merupakan Bendahara Umum Negara in daily term, BIP merupakan Bank
for unbankable institution/ company. Sebagaimana praktek di berbagai
negara, peran BIP sangat penting dalam membantu lembaga penyedia layanan publik
non kementrian yang membutuhkan pendanaan.
Ini merupakan fungsi pemerintah, dan untuk itu pemerintah tidak memungut
imbalan/ bunga sebagaimana layaknya bank.
Namun dalam perkembangannya BIP
dikembangkan dengan pola Public Private
Partnership untuk memfasilitasi pihak swasta dalam melakukan investasi,
khususnya, di bidang pembangunan infra structure. Pada saat itulah, secara
mendasar telah terjadi perubahan motif/ orientasi fungsi BIP, sehingga BIP
tidak layak lagi berada di bawah Ditjen. Perbendaharaan selaku BUN dan
diputuskan untuk ditarik di bawah kendali Sekretaris Jenderal Kementrian
Keuangan.
Namun, apa pun bentuk, peran, dan motivasi PIP, lembaga tersebut adalah unit organisasi di bidang pengelolaan investasi
Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
Seluruh dana PIP merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan yang dikelola
melalui sistem APBN.
Dengan demikian, PIP
berkewajiban menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Kementrian/ Lembaga (RKAK/L) Kementrian
Keuangan.
Sebagai satuan kerja pemerintah,
pendanaan kegiatan BLU dialokasikan dalam APBN yang memerlukan proses
pembahasan dan penetapan di lembaga legislatif (DPR).
Yang Mulia Ketua dan para
Hakim Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi dan para hadirin yang saya hormati
Dari penjelasan tersebut
diatas dapat kiranya disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1.
APBN yang merupakan kesepakatan antara Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif
diputuskan dalam suatu proses politik.
2.
Dalam penetapan APBN kedudukan Lembaga Legislatif lebih kuat
dibandingkan Lembaga Eksekutif.
3.
Semua kegiatan dan alokasi dana untuk membiayai kegiatan semua
kementrian/ lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan
penyediaan layanan publik memerlukan pembahasan dan penetapan/ persetujuan lembaga
legislatif.
4.
Pelaksanaan APBN merupakan tindak lanjut dari suatu proses politik.
5.
Oleh sebab itu, pelaksanaan APBN tidak boleh menyimpang dari penetapan
yang dilakukan oleh Lembaga Legislatif.
Selanjutnya, atas dasar
simpulan dimaksud perkenankanlah saya menyampaikan pendapat terhadap kasus yang
sedang disengketakan sebagai berikut :
1.
Pembelian saham PT NEWMONT NUSA TENGGARA
sebesar 7% oleh pihak Pemohon (Pemerintah) yang dalam hal ini dilakukan oleh
PIP harus dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran PIP selaku BLU.
2.
Rencana Bisnis dan Anggaran PIP selaku BLU sebagai bagian dari RKAK/L
Kementrian Keuangan harus dibahas dan disetujui oleh DPR, baik oleh Badan
Anggaran maupun oleh Komisi mitra kerja Kementrian Keuangan.
3. Dengan demikian, Pembelian saham PT NEWMONT NUSA TENGGARA sebesar 7% oleh pihak Pemohon (Pemerintah), yang
dalam hal ini dilakukan oleh PIP, harus dibahas dan disetujui terlebih dahulu
oleh DPR sebelum dilaksanan.
Majelis
Hakim Yang Mulia, demikianlah keterangan saya. Semoga keterangan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
dan dapat menjadi masukan serta
pertimbangan bagi Para Yang Mulia dalam memeriksa, mengadili, dan
memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara ini dengan seadil-adilnya.
Terima kasih, Yang
Mulia.
Wassalam mualaikum wr wb.
Jakarta, 04 April 2012